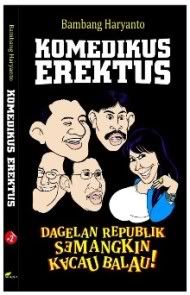Tionghoa Surabaya, Sepakbola, dan Suporter Indonesia
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner (at) yahoo.com
 “Sepak bola,” demikian kata Nelson Mandela, “merupakan aktivitas yang paling mampu mempersatukan umat manusia.”
“Sepak bola,” demikian kata Nelson Mandela, “merupakan aktivitas yang paling mampu mempersatukan umat manusia.”Merujuk negerinya dengan sejarah kelam tergencet politik apartheid yang panjang, kemudian bangkit dalam rekonsiliasi, dan di bulan Juni 2010 mendatang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010, ucapan Bapak Afrika Selatan itu terasa membiaskan kebenaran. Sepak bola memang mempersatukan dan Indonesia pun sempat merasakannya.
Eduardo Galeano, novelis asal Uruguay dalam Football in Sun and Shadow (2003), yang menulis panorama sepak bola dunia dengan kaya konteks, berdegup dan indah, telah menyandingkan nama Indonesia dalam tiga kali Piala Dunia. Tahun 1938, 1966 dan 1998.
Dirunut dari momen yang mutakhir, bara gairah Piala Dunia 1998 yang kembali diadakan di Paris, ternyata di Indonesia tersaingi oleh kobaran api, derak puing, air mata dan kematian. Peristiwa mengerikan itu akibat politik bumi hangus yang sebagian memakan korban etnis Cina, mengiringi tumbangnya diktator Soeharto.
Surut tiga puluh dua tahun sebelumnya, ketika penyelenggaraan Piala Dunia 1966 di London, Inggris, Indonesia tergenang banjir darah. Noda-noda darah itu tersembunyi mengiringi langkah sepatu lars Soeharto naik ke puncak untuk mencengkeram Indonesia.
Hanya pada tahun yang disebut pertama, 1938, nama Indonesia benar-benar disebut Galeano terkait dalam pesta sepakbola dunia di Perancis itu. Di sinilah ucapan Nelson Mandela boleh jadi punya makna bagi kita. Karena tim yang dikirim ke Perancis itu, walau di bawah bendera pemerintahan Hindia Belanda, terdiri beragam etnis bangsa.
 Oportunistis ? Sebuah buku baru yang ditulis R.N. Bayuaji berjudul Tionghoa Surabaya Dalam Sepakbola 1915-1942 (Ombak, 2010), punya cerita menarik. Utamanya, menyebutkan bahwa dalam tim tersebut terdapat pemain orang Belanda, Tionghoa dan Bumiputera (h.88).
Oportunistis ? Sebuah buku baru yang ditulis R.N. Bayuaji berjudul Tionghoa Surabaya Dalam Sepakbola 1915-1942 (Ombak, 2010), punya cerita menarik. Utamanya, menyebutkan bahwa dalam tim tersebut terdapat pemain orang Belanda, Tionghoa dan Bumiputera (h.88).Keberadaan tiga etnis tersebut memang mencerminkan trikotomi organisasi sepakbola era kolonial saat itu. NIVU (Nederlandsch Indische Voetbal Bond) untuk etnis Belanda, HNVB (Hwa Nan Voetbal Bond) bagi keturunan Tionghoa dan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) untuk kaum bumi putera. Yang menarik dicatat adalah, menjelang Piala Dunia 1938 tersebut telah terjadi perbenturan kepentingan antara NIVU versus PSSI.
“Pihak PSSI bersikukuh bahwa wakil di Piala Dunia adalah PSSI bukan NIVU, akan tetapi FIFA mengakui NIVU sebagai wakil Dutch East Indies. Ir. Soeratin (Ketua PSSI saat itu) menolak memakai nama NIVU karena ketika NIVU mempunyai hak, maka dalam penentuan komposisi materi pemain yang menentukan adalah orang-orang Belanda. Perjanjian tersebut lantas dibatalkan oleh PSSI.” (h.77-78).
Urusan sepakbola telah bercampur politik, juga nasionalisme. Bagaimana posisi etnis Tionghoa saat itu dalam urusan sepak bola ?
R.N. Bayuaji menyimpulkan, “Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kalangan sepak bola Tionghoa di Hindia Belanda…Akibat perselisihan itu, pemain Tionghoa Surabaya dapat ikut serta dalam rombongan pemain yang memperkuat Dutch East Indies (NIVU) untuk mengikuti Piala Dunia. Kesempatan yang datang mungkin saja tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, sehingga bagi sepak bola Tionghoa hal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.” (h.87).
Itukah cerminan sikap oportunistis etnis Tionghoa ? Yang senantiasa sigap mengail di kolam yang keruh ? Yang juga terjadi tidak hanya dalam kancah sepak bola, baik di jaman dulu dan juga di masa sekarang ?
Yang menonjol dalam buku yang diterbitkan berdasar skripsi karya R.N. Bayuaji di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga itu, adalah jajaran fakta upaya untuk naik kelas, upward mobility, bagi etnis Tionghoa sebagai bangsa kelas dua (bersama Arab) melalui jalur sepak bola. Bahkan terungkap ujaran betapa kaum Tionghoa saat itu dinilai “lebih Belanda dibandingkan bangsa Belanda itu sendiri.”
Sementara interaksi mereka dengan bangsa kelas tiga, kaum bumi putera, hanya muncul sekilas-sekilas dan itu pun teramat kabur dalam buku ini. Walau juga muncul jargon nasionalisme dalam sepak bola kaum Tionghoa saat itu, dengan manifestasi aksi penggalangan dana melalui pertandingan sepakbola, tetapi dana itu ternyata digunakan untuk “meringankan beban kesengsaraan” warga leluhurnya di Tiongkok Utara (h.111-112).
Jauh panggang dari api. Dalam konteks di atas, kata pengantar Freek Colombijn, antropolog lulusan Leiden dan mantan pemain bek kanan Harlemsche Football Club di Belanda, membuat saya kecewa berat. Pandangannya bahwa buku ini menekankan bahwa masyarakat Cina, melalui sepak bola, justru terintegrasi dengan masyarakat lainnya, masih jauh panggang dari api.
Entah mungkin karena keterbatasan waktu (dikejar tenggat skripsi) atau visi, interaksi antara etnis Tionghoa dan bumi putera di lapangan sepak bola di era itu sama sekali belum ia gali.
Atau justru dengan teknik reading between the line, mengungkap makna yang tersembunyi, wilayah yang tidak atau belum disentuh penulis itu boleh jadi merupakan cerminan betapa problematika antara etnis Tionghoa dan pribumi sebagai masalah laten yang belum selesai. Hingga kini.
Etnis Tionghoa yang di masa kolonial itu dipatok sebagai bemper pemerintahan Belanda, demikian juga di masa Soeharto, akhirnya stereotip yang melekat adalah kuatnya orientasi mereka untuk lebih dekat kepada penguasa daripada kepada rakyat. Mereka baru ngeh terhadap rakyat bila terjadi kerusuhan dan huru-hara berbau SARA, yang memakan korban dari mereka.
Terakhir, bagi saya yang berkomentar dari kacamata seorang suporter, buku ini juga menyiratkan betapa sejarahwan sepak bola masih belum memasukkan suporter dalam radar dan perangkat rekaman mereka. Bahkan seiring tumbuhnya perkumpulan olah raga di Surabaya oleh etnis Tionghoa saat itu, juga sepakbola, suporter menjadi latar belakang yang kabur. Penjelasan berbunyi, “Konflik yang terjadi berupa perkelahian dan kekacauan karena sepak bola, bahkan kerusuhan antarsuporter, bukanlah suatu hambatan dalam membina dunia persepakbolaan.” (h.81).
Tak ada penjelasan secara rinci, misalnya dengan mengambil rumus penulisan berita 5W+1H terkait dengan kerusuhan suporter tersebut. Apakah melibatkan suporter pendukung tim beretnis Belanda, melawan tim etnis Tionghoa, atau kaum bumi putera ? Semuanya tidak jelas. Atau sebaiknya, kalimat itu dihilangkan saja.
Dalam bingkai itu, buku ini ibarat deretan catatan sejarah jajaran papan-papan nama organisasi sepak bola. Juga nama beberapa stadion. Beberapa nama pemain sepakbola. Tetapi secara keseluruhan papan-papan itu tersalut warna pucat.
Sepi. Tak ada darah, karena nyaris tidak ada cerita-cerita tentang manusia-manusia sepakbola, dialektika dan dinamikanya. Apalagi, sekali lagi, juga tidak ada cerita tentang suporternya, walau seorang Jock Stein, legenda sepakbola Skotlandia bilang bahwa tanpa suporter sepak bola hanyalah omong kosong belaka.
Isi buku ini jelas bukan omong kosong. Mungkin saya menuntut terlalu banyak untuk sebuah karya skripsi. Mungkin itu tugas bagi penulis lain, sejarawan lain, untuk mau menulis kisah sejarah yang disebut sebagai micro history, tentang sosok individu dan jamannya, yang di era digital ini sebenarnya dapat tersaji secara mudah melalui blog-blog pribadi.
Imbauan saya, sobat-sobat para suporter, mulailah menulis sejarah Anda sendiri, dalam blog-blog Anda saat ini. Karena baru-baru ini sebuah koran nasional tiba-tiba menulis masalah mengatasi kerusuhan suporter, tetapi nampak tidak mau menjelajah apa yang pernah dilakukan dan sudah tercatat dalam sepuluh tahun terakhir mosaik-mosaik ikhtiar sebagian individu suporter Indonesia dalam berbenah diri.
Buku yang menambah rak khasanah literatur sepak bola Indonesia. Tetapi karena tidak terdengar gema suara-suara manusia dari sana, saya sebagai tukang cerita merasa tidak mampu menemukan ajaran, hikmah atau pesan yang dapat didaulat sebagai inspirasi bagi sesama pencinta sepak bola di negeri ini.
Misalnya sebagai suntikan bagi kita bersama guna berusaha mengentaskan jiwa dan raga sepak bola kita yang terlalu lama terendam di kolam kotor, akibat meruyaknya budaya korupsi di negeri ini pula.
Dengan sasaran puncak, seturut tutur Nelson Mandela, menjadikan sepak bola sebagai pemersatu dan ajang prestasi beragam etnis bangsa Indonesia guna mengangkat bangsa ini meraih prestasi terhormat di kancah dunia.
Wonogiri, 28/3/2010
si
Labels: bambang haryanto, buku sejarah, bumi putera, etnis tionghoa, freek colombijn, nasionalisme, nelson mandela, oportunistis, pssi, r.n. bayuaji, suporter indonesia, tionghoa surabaya dalam sepak bola