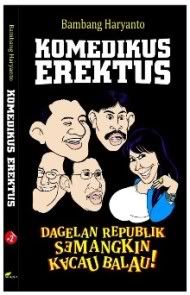Budaya Selebritis Cengkeram Jantung Sepakbola Kita
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner (at) yahoo.com

Impian saya gagal.
The Henin Syndrome hanya membuahkan kesedihan.
Kisah dongeng dua petenis Belgia yang come back dan meraih juara, tak terjadi. Kim Clijsters telah sukses di Amerika Serikat Terbuka 2009. Tetapi Justine Henin kandas di tangan Serena Wiliams di final Australia Terbuka 2010 (30/1/2010).
Toh Henin menerima kekalahan itu dengan mengesankan. Mengingatkan ujaran ratu tenis dunia era 70-an, Chris Evert : “Bila kau mampu bereaksi sama baik ketika menang atau kalah, itu prestasi yang luar biasa. Kualitas tersebut penting karena akan selalu bersamamu pada sepanjang hidup dan karena akan hadir kehidupan di luar tenis yang jauh lebih panjang dibanding kehidupan bermain tenis.”
Tak ada gurat kekecewaan di wajah Henin. Setelah memperoleh nampan perak sebagai penanda juara kedua dari legenda tenis Australia, Margaret Court, Henin antara lain mengatakan tekadnya : “Sampai jumpa tahun depan.” Ia yang selama permainan nampak condong didukung audiens, memperoleh tepuk tangan meriah dari penonton.
Sementara itu Serena Williams yang mencoba bercanda tentang tangannya yang penuh membawa piala dan boneka, “sehingga cek hadiah saya terpaksa saya tinggalkan di meja,” tidak memperoleh sambutan apa pun.
Piramida Maslow. Saat upacara itu saya baru ngeh tentang adanya perbedaan unik dalam upacara selebrasi para pemenang. Misalnya apa yang terjadi di pentas tenis Australia Terbuka itu dengan memperbandingkan, misalnya, dengan turnamen bulutangkis atau liga sepakbola di Indonesia.
Di Australia itu, hadiah uang diwujudkan berupa cek yang dimasukkan dalam amplop. Sementara di Indonesia, saya juga pernah dua kali mengalaminya sendiri di panggung tingkat nasional, nilai nominal hadiah uang dan nama sponsor selalu tertera dalam sebuah giant check yang mencolok mata.
Ironinya, oleh para fotografer media, benda satu itu justru selalu mereka usahakan untuk tidak bisa masuk dalam jepretan kamera mereka !
Apakah perbedaan itu menyimbolkan pandangan yang berbeda tentang uang. Di Australia, apakah “uang itu tidak lagi penting,” dan sementara di Indonesia, “uang adalah segala-galanya ?”
Wartawan olahraga Kompas, Samsul Hadi (30/1/2020) ketika mengupas kebobrokan penyelenggaraan olahraga sepakbola kita selama ini, telah mengutip pendapat Peter Withe yang terpajang di situs Goal.com (27/1/2010). Pria Inggris yang sukses gemilang melatih timnas Thailand tetapi gagal mengangkat prestasi timnas Indonesia, di Hotel Amara, Tanjong Pagar, Singapura (16/1/2005) dengan senang hati menuliskan tanda tangan di kaos saya yang bertuliskan “I Believe The Withe Magic, ” mengatakan hal menarik :
“Pemain Thailand termotivasi bermain demi Raja dan negara. Banyak pemain Indonesia yang menyedihkan, termotivasi oleh uang.”
Lalu saya teringat Piramida Maslow (1954) mengenai hirarki kebutuhan hidup manusia. Berdasar tesis Maslow tersebut maka motif para pemain sepakbola kita nampaknya berada pada piramida tingkat terbawah. Motif mereka bersepakbola semata demi pemenuhan kebutuhan fisiologis manusia yang bersifat primitif.
Meliputi pemenuhan agar terhindar dari rasa lapar dan haus, kebutuhan yang relatif sederhana, sekaligus mementingkan diri sendiri, dan yang paling pokok untuk mendukung kelangsungan hidup itu sendiri. Sementara pemain bola Thailand, bermain dalam tataran yang jauh lebih tinggi, di puncak Piramida Maslow : untuk aktualisasi diri.
Melihat contoh kasus beberapa klub yang berlaga di tingkat atas tetapi terlambat membayar gaji kepada pemain, membuat tuntutan primitif semacam itu dapat dimaklumi. Tetapi bagaimana kalau kebutuhan primer dan bahkan tersier mereka terpenuhi, mereka dapat memiliki rumah, mobil dan tabungan, sementara prestasi tinggi tak juga dapat mereka raih ketika berkostum tim nasional berlambangkan Garuda ?
Ini masalah isi dalam batok kepala.
Bukan semata kepala mereka yang para pemain tersebut, tetapi terutama pada kepala para pengurusnya di kantor PSSI. Para pengurus itu saya suka menyebutnya sebagai para sugar daddy, para bos-bos yang punya banyak uang.
Dari pelbagai kebijakan yang mereka tempuh kita mencatat bahwa mereka cenderung memiliki perspektif bahwa prestasi itu dapat pula mereka beli dengan uang. Pengiriman tim ke Primavera Italia dan yang terbaru ke Uruguay merupakan cerminan sikap mental para sugar daddy itu.
Solusi budaya selebritis !
Dua budaya. Kalangan sosiolog berpendapat bahwa di dunia saat ini sedang bertempur antara dua budaya. Yaitu budaya hero, pahlawan, melawan budaya pesohor, selebritis. Budaya hero bercirikan suatu upaya pencapaian prestasi dengan bekerja keras, tekun, sabar, berproses langkah demi langkah, alami dan memakan waktu.
Hal universal ini, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People (1989), berlaku untuk semua tahap kehidupan, pada semua bidang perkembangan. Apakah belajar main piano atau berkomunikasi. Juga berlaku untuk setiap individu, dalam perkawinan, keluarga, atau pun organisasi.
Prinsip atau fakta mengenai pentingnya proses ini kita fahami dan kita terima bila berlaku pada bidang yang bersifat fisik. Tetapi untuk memahaminya di bidang emosional, hubungan antar manusia dan bahkan dalam karakter pribadi, ternyata tidak mudah dan lebih sulit. Bahkan ketika pun kita memahaminya, menerimanya dan hidup selaras dengan prinsip tersebut, ternyata merupakan hal yang lebih sulit lagi.
Akibatnya, kita selalu mudah tergoda untuk mencari terobosan, jalan pintas, mengharap dengan melompati beberapa langkah vital guna menghemat waktu dan usaha, tetapi tetap mampu meraih hasil yang maksimal.
Sikap mental getol mengambil jalan pintas, itulah perwujudan budaya selebritis, yang cenderung ingin sukses secara instan dengan mengingkari proses alami suatu perkembangan. Anda ingin kaya raya tanpa perlu dibarengi kerja keras dalam waktu lama ? Maka tak ayal, mewabahlah budaya korupsi.
Ingin nampak berpendidikan tinggi, tetapi tak mau bersusah payah berkuliah dan membaca-baca literatur tebal ? Budaya jual-beli gelar akademi palsu meruyak dimana-mana. Sehingga pantaslah kalau kalangan sosiolog menyimpulkan betapa budaya selebritis itu berimpit ketat dengan budaya kriminalitas.
Sekali lagi : budaya kri-mi-na-li-tas !
Jadi, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, menjadi tidak aneh bila dalam tubuh PSSI terdapat petingginya yang pernah tersangkut dalam tindak kriminal, korupsi. Hebatnya lagi, walau mengaku gagal memimpin PSSI (Kompas, 2/2/2010), tetapi dirinya tetap saja emoh untuk mengundurkan diri.
Wonogiri, 4 Februari 2010
Labels: bambang haryanto, budaya jalan pintas, budaya selebritis, nurdin halid, peter with, piramida maslow, pssi, sepakbola indonesia, stephen r. covey, sugar daddy, thailand