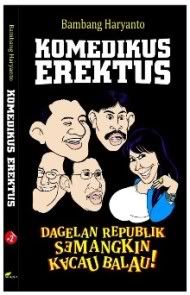Paradoks Teknologi, Splendid Entrepreneur Dan Gugatan Dari Wonogiri Bagi Sepakbola Indonesia
Oleh : Bambang HaryantoEmail : humorliner@yahoo.com
The Technology Paradox merupakan judul sampul yang provokatif dari majalah Business Week, 6/3/1995. Majalah ini saya beli di Solo hampir dua belas tahun yang lalu. Subjudulnya pun inspiratif :
“Telepon seluler menjadi hadiah gratisan. Peranti lunak dijajakan secara cuma-cuma. Komputer laptop berkemampuan sebesar komputer mainframe. Tatkala teknologi tinggi menjadi teramat murah, produsernya pun harus mencari cara-cara baru untuk meraup keuntungan. Mereka telah mendapatkannya.”
Salah satu penganut pemakaian cara-cara baru berbisnis itu antara lain taipan media, Rupert Murdoch. Bos News Corp. ini, demikian kutip Business Week, telah memunculkan istilah splendid entrepreneur untuk merujuk orang-orang yang bersenjatakan antena parabola di India untuk membajak siaran televisi satelit global StarTV milik sang baron media itu. Kemudian para wiraswastawan cerdas itu menjual siaran StarTV tersebut kepada tetangganya melalui saluran kabel.
“Kalangan yang sinis berkata bahwa pembajakan itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup Star. Kami berpendapat lain,” cetus Murdoch. Apa logikanya ? Menurutnya, para splendid entrepreneur tersebut justru berjasa memperluas pasar StarTV sehingga membuka peluang bagi Murdoch untuk menaikkan biaya pemasangan iklan di medianya.
Jalan pikiran Murdoch yang mencengangkan. Sekaligus sungguh menyenangkan ketika isi laporan utama Business Week dua belas tahun lalu itu kini menggaung kembali di kepala saya hari-hari ini. Bahkan memunculkan rasa gelitik tersendiri ketika realitas kasus yang sama telah melibatkan hidup saya sehari-hari. Yaitu tatkala bisa menikmati buah karya warga Wonogiri, yang sekaligus splendid entrepreneur, yang telah mengikuti logika Murdoch tersebut.

Dua Belas Tahun Kemudian. Paradoks teknologi telah menjungkirbalikkan norma berbisnis dalam kancah teknologi informasi masa kini. Semua inovasi kini cenderung “dijual” secara gratisan, dari layanan email seperti Hotmail dan Yahoo, fasilitas blog sampai fasilitas tayangan video YouTube.
Dua belas tahun lalu laporan majalah ini telah memunculkan istilah ekonomi atensi (attention economy), di mana semua produk gratisan itu diobral secara cerdik guna memperebutkan komoditas paling langka dan paling berharga di era digital saat ini : atensi manusia. Beredarnya video mesum Yahya Zaini-Maria Eva, pada satu sisi, adalah manifestasi ekonomi atensi.
Sosok splendid entrepreneur asal Wonogiri itu Totok namanya. Tanpa kreasi Totok tersebut dapat dipastikan penduduk kota Wonogiri sangat terbatas pilihan saluran, termasuk juga kualitas gambarnya, dalam memperoleh akses siaran televisi yang ada. Topografi kota Wonogiri yang terkepung gunung memang menjadi kendala serius bagi penangkapan siaran televisi. Bagi saya pribadi, kendala itu pasti mengisolasi saya dari peluang menonton siaran televisi yang saya sukai : pertandingan sepakbola.
Walau pun demikian, bisnis televisi kabelnya Totok dan kawan-kawan ini kadang juga perlu diingatkan. Entah karena tidak tahu, atau teledor, sekadar contoh, pada hari Selasa malam (26/12/2006) hampir saja saya tidak bisa menonton pertandingan Liga Inggris sehari sesudah Natal.
Sebenarnya pada siang harinya saya sudah berusaha ke rumahnya Totok itu. Ingin mengingatkan bahwa nanti malam ada pertandingan sepakbola. Sepulang dari Perpustakaan Umum Wonogiri, saya ingin mampir. Tetapi saya salah masuk rumah. Yang saya masuki adalah rumah yang pintunya tertutup dan salam saya tiada berbalas. Di sekitar tidak ada yang bisa saya tanyai. Saya memutuskan pulang siang itu.
Selasa malam itu Wonogiri sedang diguyur hujan deras. Tetapi sekitar 15 menit menjelang kick-off, saluran ESPN Star Sports belum muncul. Saya memutuskan untuk ke rumahnya Totok lagi. Dengan memakai payung kecil, saya memaksakan diri menembus hujan untuk menuju rumah pusat penyiaran televisi kabel a la Wonogiri ini. Payung untuk menahan sinar matahari itu agak terlalu kecil, membuat sebagian tubuh saya terciprat air hujan. Tak apalah.
Payung itu berwarna merah dan biru, di mana pada warna birunya ditaburi bintang-bintang warna putih. Pada blok warna merah dihiasi tulisan putih, “USA Atlanta 1996.” Payung ini adalah merchandise yang dibawa adik saya, Broto Happy W. ketika ia meliput Olimpiade Atlanta 1996. Jadi payung itu sudah berumur 10 tahun.
Sokurlah, di malam hari itu saya bisa menemukan rumahnya Totok. Dari balik pagar saya hanya memberikan pesan, harap saluran 7 yang kini diisi oleh stasiun televisi Trans 7, dipindah ke ESPN Star Sports. Ketika saya tiba kembali ke rumah, perjalanan menembus hujan sepanjang satu kilometer itu membawa hasil maksimal. Bisnis Totok memenuhi permintaan pelanggannya.
Sambil menikmati gorengan tempe dan tahu, juga cabai, saya bisa menikmati pertandingan yang dikenal sebagai Boxing Day itu. Baik antara Chelsea vs Reading yang seru, 2-2, mau pun Manchester United yang menekuk Wigan dengan skor akhir 3-1.
Moment of Glory. Mengikuti pertandingan sepakbola melalui media elektronik kiranya merupakan pengalaman hidup yang tidak luar biasa bagi banyak orang. Mengilas balik, ketika saya duduk di bangku SD hingga SMP, sekitar tahun 1965-1968, saya mengikutinya melalui radio. Bukan di rumah, karena keluarga kami tidak memiliki radio. Tetapi di rumah Pak Maryomo.
Ayah dari mBak Mutmainah, mas Gembuk (Bambang Sadoyo), mBak Entuk dan mBak Uci ini, termasuk orang terpandang di kampung kami dengan memiliki radio saat itu. Di depan rumahnya terdapat pohon asam yang besar, hanya sekitar 15 meter dari rumah saya. Radionya masih memakai tabung, kuno, dan belum memakai transistor. Bentuknya besar. Mereknya Philips. Setelah pertandingan usai, saya senantiasa merekonstruksi pertandingan yang terjadi dalam bentuk tulisan. Mirip perilaku wartawan olahraga.
Lewat radio pula, di tahun 1966, saya diberitahu oleh teman SD saya, Sugeng Sudewo, mengenai hasil akhir pertandingan final Piala Dunia 1966. Saat itu Inggris menjadi juara dunia setelah menaklukkan Jerman Barat. Dewo, putra dari Pak Hadisubroto ini, ketika duduk di kelas 6 SD Negeri 3 Wonogiri, adalah teman saya berbagi cerita. Saya rutin membaca serial Nogososro-Sabukinten karya SH Mintardjo dan Dewo mengikuti serial Bende Mataram, karya Herman Pratikto. Saya sering bermain ping pong di rumahnya.
Di kelas 6 yang diampu oleh Pak Narwoto, ia mendapat gurauan perjodohan model anak-anak sebagai Dewo-Karsih. Sukarsih berasal dari Bauresan. Pasangan lain yang juga dijodoh-jodohkan, yang bisa saya ingat, adalah Bodong-Anna. Bahkan merek sepeda motor BSA, dimaknai sebagai singkatan Bodong Seneng Anna.
Bodong adalah sebutan gaul untuk Priambodo. Pengalaman masa kecil yang berkesan dengannya adalah ketika saya ia bolehkan menitipkan sebutir telur bebek agar bisa ikut dierami oleh ayam babon milik Bodong ini. Ketika telur itu benar-benar menetas, saya bisa membawa pulang anak bebek itu dengan perasaan takjub sekaligus gembira.
Sementara itu Anna atau Dwianna Warpinyuliastuti, adalah putri Bapak/Ibu Suwarso. Bapak Suwarso adalah seorang tentara TNI-AD di Kodim 0728 Wonogiri, kolega ayah saya. Saya ingat, setiap kali Anna yang hitam manis dan inosen itu mendapat giliran mendongeng atau bercerita di depan kelas, dan saat ia diharuskan menunjuk murid lain sebagai pendongeng berikutnya, Anna selalu menunjuk diri saya. Saya tak tahu alasan Anna melakukan hal itu.
Selepas SD, sepertinya kami berpisah sekolah. Anna meneruskan ke SMP Negeri 2 di Bantarangin, yang hanya sekitar 50 meter dari rumahnya. Ada teman lain bilang, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang pasti, kini menjadi agen genteng Soka Kebumen dan warung soto. Seingat saya, kakak perempuannya, Johar, yang bersekolah di SMPN 1 Wonogiri. Bodong sepertinya juga masuk ke SMPN 2.
Kembali tentang Dewo. Ketika sama-sama meneruskan ke SMP Negeri 1 Wonogiri, kami berbeda kelas. Ia duduk di klas 1A dan saya di 1 B. Ketika bermain sepakbola, Dewo tampil sebagai penjaga gawang, sementara saya sebagai penyerang. Setiap kali saya jalan kaki pagi dan melewati lapangan Sukorejo, terutama di gawang sebelah barat, kenangan masa kecil itu seolah tertayang kembali.
Saat itu saya telah melakukan solo run, ibarat Jorge Buruchaga setelah memperoleh umpan jarak jauh kaki kiri sang jenius Maradona pada Piala Dunia 1986, saya berhasil menaklukkan gawang yang dikawal Dewo, teman saya tersebut. Peristiwa ini merupakan moment of glory, mungkin satu-satunya, yang masih berbekas ketika saya mampu bermain sepakbola. Setelah itu, kiranya saya tidak bermain sepakbola lagi.
Dari enam anak laki-laki keluarga Kastanto Hendrowiharso yang pernah menekuni sepakbola hanyalah Bari, anak ketiga, dan anak nomor enam, Broto Happy W., yang kini masih bermain sepakbola untuk membela tim Tabloid BOLA, tempatnya ia bekerja. Anak kesepuluh, Basnendar HPS, menekuni basket.
Saya, anak pertama, dan Mayor Haristanto, anak keempat, sejak tahun 2000 menjadi aktivis kelompok suporter sepakbola Pasoepati dari Solo.

Wong Wonogiri Masuk Televisi. Sebagai suporter sepakbola, saya (nomor dua dari kanan) dan Mayor Haristanto (nomor tiga dari kanan) dan Sengkut Pandega, pernah menjadi nara sumber acara One Stop Football dari stasiun televisi TV7 Jakarta.
Dengan dipandu host Deasy Noviyanti, kiri, kami membincangkan peranan suporter Indonesia dalam pertandingan leg I Final Piala Tiger 2004/2005 antara tuan rumah Indonesia vs Singapura, 8 Januari 2005. Seminggu kemudian, saya dan Mayor meneruskan dukungan kepada timnas Indonesia pada leg 2 di Stadion Kallang, Singapura.
Gugatan dari Wonogiri. Bukti kecil kecintaan dan atensi saya terhadap sepakbola, selain meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli (2000), mengelola blog Suporter Indonesia ini, dan sebagai pencetus komunitas Epistoholik Indonesia saya juga terus menulis surat-surat pembaca. Sebagai contoh di bawah ini :
Hancurnya Sepakbola Melayu
Dimuat Koran Tempo, Rabu, 22 November 2006
Tim nasional Indonesia di bawah umur 23 tahun digunduli 6-0 di penyisihan sepakbola Asian Games 2006 di Qatar. Padahal mereka sempat berlatih 4 bulan, menghabiskan biaya 28 milyar rupiah di Belanda. Asisten pelatih Bambang Nurdiansyah seperti dikutip wartawan Kompas, Samsul Hadi, yang ditanyai oleh BBC (20/11) mengabarkan bahwa Ferry Rotinsulu dan kawan-kawan itu bermain dengan “gaya sepakbola Melayu, bukan sepakbola Eropa.”
Apa yang ia maksud sebagai sepakbola Melayu ? Perlu penjelasan lebih lanjut. Yang pasti, dalam pertandingan tersebut dua pemain kita kena kartu merah dan enam pemain kena kartu kuning. Itukah cerminan “sepakbola Melayu” yang berarti pemain-pemain kita tidak mengindahkan peraturan bermain sepakbola yang berlaku secara universal ?
Tanggal 6/11/2006, di Solo, saya mewawancarai Ponaryo Astaman, kapten timnas senior kita, terkait pernyataan dia yang juga pernah dikutip oleh BBC. Kata Ponaryo, sepanjang menjadi pemain sepakbola dirinya tidak pernah sama sekali memperoleh sosialisasi mengenai pelbagai peraturan dalam bermain sepakbola. Para pemain kita, ujarnya lebih lanjut dan bagi saya sangat mengherankan, mematuhi peraturan bermain sepakbola hanya berdasar pengalaman dan instink masing-masing pribadi, yaitu ketika mereka memperoleh hukuman dari wasit. Realitas yang memprihatinkan !
Hancurnya timnas U-23 di ajang Asian Games 2006 antara lain akibat hukuman dua kartu merah dan enam kartu kuning, walau mereka berlatih di Belanda 4 bulan sekali pun, hanya menunjukkan bahwa mengubah teknik dan mental pesepakbola kita bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Sikap mental suka ambil jalan pintas yang dianut para petinggi PSSI, terutama yang memiliki pendekatan bahwa uang menentukan segalanya, kini terantuk oleh bukti kegagalan yang benar-benar nyata. Uang bukan segala-galanya, Bung Nurdin Halid dan Bung Nirwan Bakrie. Selamat berintrospeksi.
Bambang Haryanto
Wonogiri 57612
Ketika hendak merampungkan tulisan ini untuk blog saya lainnya yang mempromosikan manfaat olahraga jalan kaki, The Morning Walker, saya memperoleh telepon tak terduga dari Hilman, wartawan Kantor Berita Radio 68H Jakarta. Hilman meminta saya untuk menjadi salah satu nara sumber dalam acara perbincangan radio bertopik sepakbola Indonesia, Jumat malam, 5 Januari 2007 mendatang.
Kalau acara ini jadi berlangsung, berarti akan dua kali warga Wonogiri yang masih tinggal di Wonogiri ini, mendapat kehormatan untuk ikut berbicara langsung di radio di forum nasional.
Bagi saya, fenomena di atas senantiasa mengingatkan kesaktian ucapan sejarawan dan Pustakawan Konggres AS, Daniel Boorstin, bahwa setiap kemajuan teknologi komunikasi akan mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Apakah hal yang saya lakoni ini bisa termasuk sebagai fenomena the technology paradox juga ?
Wonogiri, 1-4 Januari 2007
si
Oleh : Bambang HaryantoEmail : humorliner@yahoo.com
The Technology Paradox merupakan judul sampul yang provokatif dari majalah Business Week, 6/3/1995. Majalah ini saya beli di Solo hampir dua belas tahun yang lalu. Subjudulnya pun inspiratif :
“Telepon seluler menjadi hadiah gratisan. Peranti lunak dijajakan secara cuma-cuma. Komputer laptop berkemampuan sebesar komputer mainframe. Tatkala teknologi tinggi menjadi teramat murah, produsernya pun harus mencari cara-cara baru untuk meraup keuntungan. Mereka telah mendapatkannya.”
Salah satu penganut pemakaian cara-cara baru berbisnis itu antara lain taipan media, Rupert Murdoch. Bos News Corp. ini, demikian kutip Business Week, telah memunculkan istilah splendid entrepreneur untuk merujuk orang-orang yang bersenjatakan antena parabola di India untuk membajak siaran televisi satelit global StarTV milik sang baron media itu. Kemudian para wiraswastawan cerdas itu menjual siaran StarTV tersebut kepada tetangganya melalui saluran kabel.
“Kalangan yang sinis berkata bahwa pembajakan itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup Star. Kami berpendapat lain,” cetus Murdoch. Apa logikanya ? Menurutnya, para splendid entrepreneur tersebut justru berjasa memperluas pasar StarTV sehingga membuka peluang bagi Murdoch untuk menaikkan biaya pemasangan iklan di medianya.
Jalan pikiran Murdoch yang mencengangkan. Sekaligus sungguh menyenangkan ketika isi laporan utama Business Week dua belas tahun lalu itu kini menggaung kembali di kepala saya hari-hari ini. Bahkan memunculkan rasa gelitik tersendiri ketika realitas kasus yang sama telah melibatkan hidup saya sehari-hari. Yaitu tatkala bisa menikmati buah karya warga Wonogiri, yang sekaligus splendid entrepreneur, yang telah mengikuti logika Murdoch tersebut.

Dua Belas Tahun Kemudian. Paradoks teknologi telah menjungkirbalikkan norma berbisnis dalam kancah teknologi informasi masa kini. Semua inovasi kini cenderung “dijual” secara gratisan, dari layanan email seperti Hotmail dan Yahoo, fasilitas blog sampai fasilitas tayangan video YouTube.
Dua belas tahun lalu laporan majalah ini telah memunculkan istilah ekonomi atensi (attention economy), di mana semua produk gratisan itu diobral secara cerdik guna memperebutkan komoditas paling langka dan paling berharga di era digital saat ini : atensi manusia. Beredarnya video mesum Yahya Zaini-Maria Eva, pada satu sisi, adalah manifestasi ekonomi atensi.
Sosok splendid entrepreneur asal Wonogiri itu Totok namanya. Tanpa kreasi Totok tersebut dapat dipastikan penduduk kota Wonogiri sangat terbatas pilihan saluran, termasuk juga kualitas gambarnya, dalam memperoleh akses siaran televisi yang ada. Topografi kota Wonogiri yang terkepung gunung memang menjadi kendala serius bagi penangkapan siaran televisi. Bagi saya pribadi, kendala itu pasti mengisolasi saya dari peluang menonton siaran televisi yang saya sukai : pertandingan sepakbola.
Walau pun demikian, bisnis televisi kabelnya Totok dan kawan-kawan ini kadang juga perlu diingatkan. Entah karena tidak tahu, atau teledor, sekadar contoh, pada hari Selasa malam (26/12/2006) hampir saja saya tidak bisa menonton pertandingan Liga Inggris sehari sesudah Natal.
Sebenarnya pada siang harinya saya sudah berusaha ke rumahnya Totok itu. Ingin mengingatkan bahwa nanti malam ada pertandingan sepakbola. Sepulang dari Perpustakaan Umum Wonogiri, saya ingin mampir. Tetapi saya salah masuk rumah. Yang saya masuki adalah rumah yang pintunya tertutup dan salam saya tiada berbalas. Di sekitar tidak ada yang bisa saya tanyai. Saya memutuskan pulang siang itu.
Selasa malam itu Wonogiri sedang diguyur hujan deras. Tetapi sekitar 15 menit menjelang kick-off, saluran ESPN Star Sports belum muncul. Saya memutuskan untuk ke rumahnya Totok lagi. Dengan memakai payung kecil, saya memaksakan diri menembus hujan untuk menuju rumah pusat penyiaran televisi kabel a la Wonogiri ini. Payung untuk menahan sinar matahari itu agak terlalu kecil, membuat sebagian tubuh saya terciprat air hujan. Tak apalah.
Payung itu berwarna merah dan biru, di mana pada warna birunya ditaburi bintang-bintang warna putih. Pada blok warna merah dihiasi tulisan putih, “USA Atlanta 1996.” Payung ini adalah merchandise yang dibawa adik saya, Broto Happy W. ketika ia meliput Olimpiade Atlanta 1996. Jadi payung itu sudah berumur 10 tahun.
Sokurlah, di malam hari itu saya bisa menemukan rumahnya Totok. Dari balik pagar saya hanya memberikan pesan, harap saluran 7 yang kini diisi oleh stasiun televisi Trans 7, dipindah ke ESPN Star Sports. Ketika saya tiba kembali ke rumah, perjalanan menembus hujan sepanjang satu kilometer itu membawa hasil maksimal. Bisnis Totok memenuhi permintaan pelanggannya.
Sambil menikmati gorengan tempe dan tahu, juga cabai, saya bisa menikmati pertandingan yang dikenal sebagai Boxing Day itu. Baik antara Chelsea vs Reading yang seru, 2-2, mau pun Manchester United yang menekuk Wigan dengan skor akhir 3-1.
Moment of Glory. Mengikuti pertandingan sepakbola melalui media elektronik kiranya merupakan pengalaman hidup yang tidak luar biasa bagi banyak orang. Mengilas balik, ketika saya duduk di bangku SD hingga SMP, sekitar tahun 1965-1968, saya mengikutinya melalui radio. Bukan di rumah, karena keluarga kami tidak memiliki radio. Tetapi di rumah Pak Maryomo.
Ayah dari mBak Mutmainah, mas Gembuk (Bambang Sadoyo), mBak Entuk dan mBak Uci ini, termasuk orang terpandang di kampung kami dengan memiliki radio saat itu. Di depan rumahnya terdapat pohon asam yang besar, hanya sekitar 15 meter dari rumah saya. Radionya masih memakai tabung, kuno, dan belum memakai transistor. Bentuknya besar. Mereknya Philips. Setelah pertandingan usai, saya senantiasa merekonstruksi pertandingan yang terjadi dalam bentuk tulisan. Mirip perilaku wartawan olahraga.
Lewat radio pula, di tahun 1966, saya diberitahu oleh teman SD saya, Sugeng Sudewo, mengenai hasil akhir pertandingan final Piala Dunia 1966. Saat itu Inggris menjadi juara dunia setelah menaklukkan Jerman Barat. Dewo, putra dari Pak Hadisubroto ini, ketika duduk di kelas 6 SD Negeri 3 Wonogiri, adalah teman saya berbagi cerita. Saya rutin membaca serial Nogososro-Sabukinten karya SH Mintardjo dan Dewo mengikuti serial Bende Mataram, karya Herman Pratikto. Saya sering bermain ping pong di rumahnya.
Di kelas 6 yang diampu oleh Pak Narwoto, ia mendapat gurauan perjodohan model anak-anak sebagai Dewo-Karsih. Sukarsih berasal dari Bauresan. Pasangan lain yang juga dijodoh-jodohkan, yang bisa saya ingat, adalah Bodong-Anna. Bahkan merek sepeda motor BSA, dimaknai sebagai singkatan Bodong Seneng Anna.
Bodong adalah sebutan gaul untuk Priambodo. Pengalaman masa kecil yang berkesan dengannya adalah ketika saya ia bolehkan menitipkan sebutir telur bebek agar bisa ikut dierami oleh ayam babon milik Bodong ini. Ketika telur itu benar-benar menetas, saya bisa membawa pulang anak bebek itu dengan perasaan takjub sekaligus gembira.
Sementara itu Anna atau Dwianna Warpinyuliastuti, adalah putri Bapak/Ibu Suwarso. Bapak Suwarso adalah seorang tentara TNI-AD di Kodim 0728 Wonogiri, kolega ayah saya. Saya ingat, setiap kali Anna yang hitam manis dan inosen itu mendapat giliran mendongeng atau bercerita di depan kelas, dan saat ia diharuskan menunjuk murid lain sebagai pendongeng berikutnya, Anna selalu menunjuk diri saya. Saya tak tahu alasan Anna melakukan hal itu.
Selepas SD, sepertinya kami berpisah sekolah. Anna meneruskan ke SMP Negeri 2 di Bantarangin, yang hanya sekitar 50 meter dari rumahnya. Ada teman lain bilang, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang pasti, kini menjadi agen genteng Soka Kebumen dan warung soto. Seingat saya, kakak perempuannya, Johar, yang bersekolah di SMPN 1 Wonogiri. Bodong sepertinya juga masuk ke SMPN 2.
Kembali tentang Dewo. Ketika sama-sama meneruskan ke SMP Negeri 1 Wonogiri, kami berbeda kelas. Ia duduk di klas 1A dan saya di 1 B. Ketika bermain sepakbola, Dewo tampil sebagai penjaga gawang, sementara saya sebagai penyerang. Setiap kali saya jalan kaki pagi dan melewati lapangan Sukorejo, terutama di gawang sebelah barat, kenangan masa kecil itu seolah tertayang kembali.
Saat itu saya telah melakukan solo run, ibarat Jorge Buruchaga setelah memperoleh umpan jarak jauh kaki kiri sang jenius Maradona pada Piala Dunia 1986, saya berhasil menaklukkan gawang yang dikawal Dewo, teman saya tersebut. Peristiwa ini merupakan moment of glory, mungkin satu-satunya, yang masih berbekas ketika saya mampu bermain sepakbola. Setelah itu, kiranya saya tidak bermain sepakbola lagi.
Dari enam anak laki-laki keluarga Kastanto Hendrowiharso yang pernah menekuni sepakbola hanyalah Bari, anak ketiga, dan anak nomor enam, Broto Happy W., yang kini masih bermain sepakbola untuk membela tim Tabloid BOLA, tempatnya ia bekerja. Anak kesepuluh, Basnendar HPS, menekuni basket.
Saya, anak pertama, dan Mayor Haristanto, anak keempat, sejak tahun 2000 menjadi aktivis kelompok suporter sepakbola Pasoepati dari Solo.

Wong Wonogiri Masuk Televisi. Sebagai suporter sepakbola, saya (nomor dua dari kanan) dan Mayor Haristanto (nomor tiga dari kanan) dan Sengkut Pandega, pernah menjadi nara sumber acara One Stop Football dari stasiun televisi TV7 Jakarta.
Dengan dipandu host Deasy Noviyanti, kiri, kami membincangkan peranan suporter Indonesia dalam pertandingan leg I Final Piala Tiger 2004/2005 antara tuan rumah Indonesia vs Singapura, 8 Januari 2005. Seminggu kemudian, saya dan Mayor meneruskan dukungan kepada timnas Indonesia pada leg 2 di Stadion Kallang, Singapura.
Gugatan dari Wonogiri. Bukti kecil kecintaan dan atensi saya terhadap sepakbola, selain meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli (2000), mengelola blog Suporter Indonesia ini, dan sebagai pencetus komunitas Epistoholik Indonesia saya juga terus menulis surat-surat pembaca. Sebagai contoh di bawah ini :
Hancurnya Sepakbola Melayu
Dimuat Koran Tempo, Rabu, 22 November 2006
Tim nasional Indonesia di bawah umur 23 tahun digunduli 6-0 di penyisihan sepakbola Asian Games 2006 di Qatar. Padahal mereka sempat berlatih 4 bulan, menghabiskan biaya 28 milyar rupiah di Belanda. Asisten pelatih Bambang Nurdiansyah seperti dikutip wartawan Kompas, Samsul Hadi, yang ditanyai oleh BBC (20/11) mengabarkan bahwa Ferry Rotinsulu dan kawan-kawan itu bermain dengan “gaya sepakbola Melayu, bukan sepakbola Eropa.”
Apa yang ia maksud sebagai sepakbola Melayu ? Perlu penjelasan lebih lanjut. Yang pasti, dalam pertandingan tersebut dua pemain kita kena kartu merah dan enam pemain kena kartu kuning. Itukah cerminan “sepakbola Melayu” yang berarti pemain-pemain kita tidak mengindahkan peraturan bermain sepakbola yang berlaku secara universal ?
Tanggal 6/11/2006, di Solo, saya mewawancarai Ponaryo Astaman, kapten timnas senior kita, terkait pernyataan dia yang juga pernah dikutip oleh BBC. Kata Ponaryo, sepanjang menjadi pemain sepakbola dirinya tidak pernah sama sekali memperoleh sosialisasi mengenai pelbagai peraturan dalam bermain sepakbola. Para pemain kita, ujarnya lebih lanjut dan bagi saya sangat mengherankan, mematuhi peraturan bermain sepakbola hanya berdasar pengalaman dan instink masing-masing pribadi, yaitu ketika mereka memperoleh hukuman dari wasit. Realitas yang memprihatinkan !
Hancurnya timnas U-23 di ajang Asian Games 2006 antara lain akibat hukuman dua kartu merah dan enam kartu kuning, walau mereka berlatih di Belanda 4 bulan sekali pun, hanya menunjukkan bahwa mengubah teknik dan mental pesepakbola kita bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Sikap mental suka ambil jalan pintas yang dianut para petinggi PSSI, terutama yang memiliki pendekatan bahwa uang menentukan segalanya, kini terantuk oleh bukti kegagalan yang benar-benar nyata. Uang bukan segala-galanya, Bung Nurdin Halid dan Bung Nirwan Bakrie. Selamat berintrospeksi.
Bambang Haryanto
Wonogiri 57612
Ketika hendak merampungkan tulisan ini untuk blog saya lainnya yang mempromosikan manfaat olahraga jalan kaki, The Morning Walker, saya memperoleh telepon tak terduga dari Hilman, wartawan Kantor Berita Radio 68H Jakarta. Hilman meminta saya untuk menjadi salah satu nara sumber dalam acara perbincangan radio bertopik sepakbola Indonesia, Jumat malam, 5 Januari 2007 mendatang.
Kalau acara ini jadi berlangsung, berarti akan dua kali warga Wonogiri yang masih tinggal di Wonogiri ini, mendapat kehormatan untuk ikut berbicara langsung di radio di forum nasional.
Bagi saya, fenomena di atas senantiasa mengingatkan kesaktian ucapan sejarawan dan Pustakawan Konggres AS, Daniel Boorstin, bahwa setiap kemajuan teknologi komunikasi akan mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Apakah hal yang saya lakoni ini bisa termasuk sebagai fenomena the technology paradox juga ?
Wonogiri, 1-4 Januari 2007
si