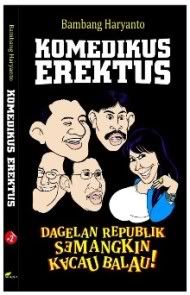Budaya Jawa dan Kekerasan Sepakbola
Oleh : Bambang Haryanto
Filsuf Perancis Jean Paul Sartre (1905-1980) pernah bilang, dalam sepakbola semuanya jadi rumit karena hadirnya pemain lawan. Dalam konteks Indonesia, sepakbola makin bertambah rumit karena hadirnya suporter tim yang bertanding, sehingga melahirkan lelucon betapa Indonesia pantas disebut sebagai negara sarang teroris. Buktinya, mereka legal berkumpul di stadion-stadion, juga leluasa melakukan aksi teror ketika tim yang ia dukung kalah.
Aksi teror dan kerusuhan suporter di Jawa Tengah meledak lagi (12/3/2006) di Jepara. Sebagai suporter dan football flaneur, istilah dari penyair Perancis, Charles Baudelaire (1821–1867) untuk turis bola yang gemar menjelajah kota untuk nonton sepakbola (di Pulau Jawa sampai Singapura), saya pribadi kenyang menemui aksi-aksi brutal suporter sepakbola Indonesia. Tetapi hal buruk tersebut senyatanya tak hanya meledak di masa kini.
Adalah Freek Colombijn, antropolog lulusan Leiden, mantan pemain Harlemsche Football Club Belanda, secara tajam mengungkap borok tindak kekerasan dunia suporter sepakbola Indonesia sejak jaman kolonial hingga kini. Dalam tulisannya "View from the Periphery : Football in Indonesia" dalam buku Garry Armstrong dan Richard Giulianotti (ed.), Football Cultures and Identities (1999), ia memakai pisau bedah dari perspektif budaya dan politik dalam analisis yang provokatif.
Ditilik dari kajian budaya, menurutnya, tidak dapat diingkari bahwa Indonesia kuat dipengaruhi budaya suku mayoritas, suku Jawa. Budaya Jawa memiliki pandangan ketat mengenai pentingnya keselarasan. Perasaan yang terinternalisasi secara mendalam dalam jiwa orang Jawa adalah kepekaan untuk tidak dipermalukan di muka umum.
Perasaan demikian memupuk konformitas, pengendalian tingkah laku dan menjaga ketat harmoni sosial. Konflik yang terjadi diredam sekuat tenaga. Reaksi normal setiap orang Jawa dalam menanggapi konflik adalah penghindaran, wegah rame, dan mediasi oleh fihak ketiga. Apabila meletus konflik, terutama ketika saling ejek dan saling hina terjadi, maka yang muncul adalah perasaan malu dan kehilangan muka.
Dengan landasan sikap interaksi antarmanusia tipikal seperti itu, membuat pertandingan sepakbola menjadi problematis. Sebab sepakbola adalah konflik eksplisit, dimana seseorang sangat mudah untuk merasa dihinakan. Adanya tackle keras, trik licin mengecoh lawan, sampai keputusan wasit yang mudah ditafsirkan secara beragam, jelas membuat penghindaran menjadi hal mustahil. Apalagi ketegangan itu diperburuk oleh fakta bahwa tindak penghinaan tersebut tidak hanya berlangsung di muka umum, tetapi nyata-nyata di depan ribuan pasang mata. Reaksi tipikal orang Jawa ketika dibawah tekanan semacam itu adalah ledakan kemarahan dan amuk tindak kekerasan.
Tesis di atas dapat dinilai parsial dan hipotetis. Karena argumen yang sama kurang meyakinkan bila diterapkan untuk kelompok etnis Indonesia lainnya, yang juga memunculkan tindak kekerasan serupa dalam teater sepakbola. Idealnya kemudian, penjelasan secara kultural tadi direntang dengan menggambarkan kesejajaran secara spekulatif antara sepakbola dengan budaya politik, sehingga mencakup pemain dan suporter dari semua latar belakang etnis di Indonesia.
Kalah dan Amuk
Dalam budaya demokrasi, kalah-menang secara fair play merupakan bagian sah suatu kompetisi. Di pentas Piala Dunia 2002 kita diberi keteladanan ketika tuan rumah Korea Selatan atau Jepang mengalami kekalahan, ternyata tidak terjadi kerusuhan sama sekali. Hal sebaliknya justru meletus kerusuhan di Moskwa ketika Rusia dikalahkan oleh Hidetoshi Nakata dan kawan-kawan.
Sementara itu di pentas sepakbola Indonesia, kerusuhan masih mudah meruyak ketika suatu tim mengalami kekalahan. Realitas ini menegaskan betapa dalam masyarakat non-madani, bahwa ide mengenai kompetisi yang selalu melibatkan konflik, belum berurat dan berakar. Bahkan perilaku menjunjung tinggi sportivitas dipandang sebagai hal bodoh. Teater sepakbola Indonesia kaya dengan contoh pelecehan terhadap sportivitas olahraga.
Misalnya dalam pertandingan terakhir putaran kedua Kompetisi Perserikatan PSSI Wilayah Timur 1988, tuan rumah Persebaya digulung Persipura dengan skor fantastis, 0 - 12. Persipura dengan kemenangan itu berarti menyisihkan peluang PSIS Semarang sebagai juara bertahan 1986/1987 untuk berlaga ke Senayan. Tetapi kemenangan fantastis itu, semua publik sepakbola mengetahuinya, merupakan kemenangan yang tidak wajar, diatur para eksekutif kedua tim perserikatan tersebut.
Dalam perempat-final Piala Tiger 1998 di Hanoi, Vietnam, terjadi peristiwa aib yang melibatkan tim nasional Indonesia. Peristiwa hitam itu terjadi ketika tim yang bertanding, baik tim Thailand atau pun Indonesia, sama-sama tidak menggubris etika dan roh olahraga itu sendiri, yaitu sportivitas.
Kedua tim berusaha mati-matian agar memperoleh kekalahan pada akhir pertandingan. Tujuannya, agar terhindar bertemu tuan rumah Vietnam di semi final. Saat skor 2-2 pada perpanjangan waktu, pemain Indonesia Mursyid Effendi menembak ke gawang timnya sendiri. Kiper Indonesia tidak berusaha menepis. Justru banyak pemain Thailand berusaha menjaga gawang timnas Indonesia agar tidak kebobolan.
Semua ilustrasi menyedihkan itu menunjukkan semangat berkompetisi secara fair play masih impian langka di Indonesia. Berdasar pendapat banyak ahli, memang itulah cermin sejati bangsa Indonesia yang lebih condong sebagai sosok masyarakat non-madani ketimbang masyarakat yang demokratis. Kalau terus seperti ini, kapan Indonesia bisa masuk Piala Dunia ? Antonio Gramsci pernah bilang, sepakbola merupakan model masyarakat individualistik yang membutuhkan prakarsa, kompetisi dan konflik. Tetapi segalanya diatur oleh peraturan tidak tertulis yaitu hukum fair play.
Mari kita introspeksi diri. Apakah masyarakat kita selama ini telah kondusif untuk mekarnya segala prakarsa, berbudaya sehat dalam berkompetisi, arif menyelesaikan beragam konflik, sekaligus patuh terhadap segala peraturan tertulis dan tidak tertulis secara konsekuen ?
Selama kita belum mengalami perubahan budaya seperti disyaratkan Gramsci, jangan harap prestasi sepakbola kita bisa ikut berbicara di pentas dunia. Hari-hari mati prestasi sepakbola Indonesia masih teramat panjang sekali. Dan kerusuhan antarsuporter seperti yang meledak di Jepara itu pasti masih terus terulang dan terulang kembali ! (Artikel ini dengan penyuntingan telah dimuat di Harian Kompas Jawa Tengah, 4 April 2006).
si
Oleh : Bambang Haryanto
Filsuf Perancis Jean Paul Sartre (1905-1980) pernah bilang, dalam sepakbola semuanya jadi rumit karena hadirnya pemain lawan. Dalam konteks Indonesia, sepakbola makin bertambah rumit karena hadirnya suporter tim yang bertanding, sehingga melahirkan lelucon betapa Indonesia pantas disebut sebagai negara sarang teroris. Buktinya, mereka legal berkumpul di stadion-stadion, juga leluasa melakukan aksi teror ketika tim yang ia dukung kalah.
Aksi teror dan kerusuhan suporter di Jawa Tengah meledak lagi (12/3/2006) di Jepara. Sebagai suporter dan football flaneur, istilah dari penyair Perancis, Charles Baudelaire (1821–1867) untuk turis bola yang gemar menjelajah kota untuk nonton sepakbola (di Pulau Jawa sampai Singapura), saya pribadi kenyang menemui aksi-aksi brutal suporter sepakbola Indonesia. Tetapi hal buruk tersebut senyatanya tak hanya meledak di masa kini.
Adalah Freek Colombijn, antropolog lulusan Leiden, mantan pemain Harlemsche Football Club Belanda, secara tajam mengungkap borok tindak kekerasan dunia suporter sepakbola Indonesia sejak jaman kolonial hingga kini. Dalam tulisannya "View from the Periphery : Football in Indonesia" dalam buku Garry Armstrong dan Richard Giulianotti (ed.), Football Cultures and Identities (1999), ia memakai pisau bedah dari perspektif budaya dan politik dalam analisis yang provokatif.
Ditilik dari kajian budaya, menurutnya, tidak dapat diingkari bahwa Indonesia kuat dipengaruhi budaya suku mayoritas, suku Jawa. Budaya Jawa memiliki pandangan ketat mengenai pentingnya keselarasan. Perasaan yang terinternalisasi secara mendalam dalam jiwa orang Jawa adalah kepekaan untuk tidak dipermalukan di muka umum.
Perasaan demikian memupuk konformitas, pengendalian tingkah laku dan menjaga ketat harmoni sosial. Konflik yang terjadi diredam sekuat tenaga. Reaksi normal setiap orang Jawa dalam menanggapi konflik adalah penghindaran, wegah rame, dan mediasi oleh fihak ketiga. Apabila meletus konflik, terutama ketika saling ejek dan saling hina terjadi, maka yang muncul adalah perasaan malu dan kehilangan muka.
Dengan landasan sikap interaksi antarmanusia tipikal seperti itu, membuat pertandingan sepakbola menjadi problematis. Sebab sepakbola adalah konflik eksplisit, dimana seseorang sangat mudah untuk merasa dihinakan. Adanya tackle keras, trik licin mengecoh lawan, sampai keputusan wasit yang mudah ditafsirkan secara beragam, jelas membuat penghindaran menjadi hal mustahil. Apalagi ketegangan itu diperburuk oleh fakta bahwa tindak penghinaan tersebut tidak hanya berlangsung di muka umum, tetapi nyata-nyata di depan ribuan pasang mata. Reaksi tipikal orang Jawa ketika dibawah tekanan semacam itu adalah ledakan kemarahan dan amuk tindak kekerasan.
Tesis di atas dapat dinilai parsial dan hipotetis. Karena argumen yang sama kurang meyakinkan bila diterapkan untuk kelompok etnis Indonesia lainnya, yang juga memunculkan tindak kekerasan serupa dalam teater sepakbola. Idealnya kemudian, penjelasan secara kultural tadi direntang dengan menggambarkan kesejajaran secara spekulatif antara sepakbola dengan budaya politik, sehingga mencakup pemain dan suporter dari semua latar belakang etnis di Indonesia.
Kalah dan Amuk
Dalam budaya demokrasi, kalah-menang secara fair play merupakan bagian sah suatu kompetisi. Di pentas Piala Dunia 2002 kita diberi keteladanan ketika tuan rumah Korea Selatan atau Jepang mengalami kekalahan, ternyata tidak terjadi kerusuhan sama sekali. Hal sebaliknya justru meletus kerusuhan di Moskwa ketika Rusia dikalahkan oleh Hidetoshi Nakata dan kawan-kawan.
Sementara itu di pentas sepakbola Indonesia, kerusuhan masih mudah meruyak ketika suatu tim mengalami kekalahan. Realitas ini menegaskan betapa dalam masyarakat non-madani, bahwa ide mengenai kompetisi yang selalu melibatkan konflik, belum berurat dan berakar. Bahkan perilaku menjunjung tinggi sportivitas dipandang sebagai hal bodoh. Teater sepakbola Indonesia kaya dengan contoh pelecehan terhadap sportivitas olahraga.
Misalnya dalam pertandingan terakhir putaran kedua Kompetisi Perserikatan PSSI Wilayah Timur 1988, tuan rumah Persebaya digulung Persipura dengan skor fantastis, 0 - 12. Persipura dengan kemenangan itu berarti menyisihkan peluang PSIS Semarang sebagai juara bertahan 1986/1987 untuk berlaga ke Senayan. Tetapi kemenangan fantastis itu, semua publik sepakbola mengetahuinya, merupakan kemenangan yang tidak wajar, diatur para eksekutif kedua tim perserikatan tersebut.
Dalam perempat-final Piala Tiger 1998 di Hanoi, Vietnam, terjadi peristiwa aib yang melibatkan tim nasional Indonesia. Peristiwa hitam itu terjadi ketika tim yang bertanding, baik tim Thailand atau pun Indonesia, sama-sama tidak menggubris etika dan roh olahraga itu sendiri, yaitu sportivitas.
Kedua tim berusaha mati-matian agar memperoleh kekalahan pada akhir pertandingan. Tujuannya, agar terhindar bertemu tuan rumah Vietnam di semi final. Saat skor 2-2 pada perpanjangan waktu, pemain Indonesia Mursyid Effendi menembak ke gawang timnya sendiri. Kiper Indonesia tidak berusaha menepis. Justru banyak pemain Thailand berusaha menjaga gawang timnas Indonesia agar tidak kebobolan.
Semua ilustrasi menyedihkan itu menunjukkan semangat berkompetisi secara fair play masih impian langka di Indonesia. Berdasar pendapat banyak ahli, memang itulah cermin sejati bangsa Indonesia yang lebih condong sebagai sosok masyarakat non-madani ketimbang masyarakat yang demokratis. Kalau terus seperti ini, kapan Indonesia bisa masuk Piala Dunia ? Antonio Gramsci pernah bilang, sepakbola merupakan model masyarakat individualistik yang membutuhkan prakarsa, kompetisi dan konflik. Tetapi segalanya diatur oleh peraturan tidak tertulis yaitu hukum fair play.
Mari kita introspeksi diri. Apakah masyarakat kita selama ini telah kondusif untuk mekarnya segala prakarsa, berbudaya sehat dalam berkompetisi, arif menyelesaikan beragam konflik, sekaligus patuh terhadap segala peraturan tertulis dan tidak tertulis secara konsekuen ?
Selama kita belum mengalami perubahan budaya seperti disyaratkan Gramsci, jangan harap prestasi sepakbola kita bisa ikut berbicara di pentas dunia. Hari-hari mati prestasi sepakbola Indonesia masih teramat panjang sekali. Dan kerusuhan antarsuporter seperti yang meledak di Jepara itu pasti masih terus terulang dan terulang kembali ! (Artikel ini dengan penyuntingan telah dimuat di Harian Kompas Jawa Tengah, 4 April 2006).
si