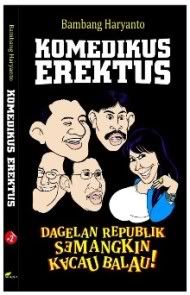Globalisasi dan Sepakbola Indonesia
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
Nasionalisme jadi titik lemah, achilles heel, sepakbola Singapura. Begitu setidaknya di mata suporter sepakbola Indonesia di Stadion Nasional Kallang pada final leg kedua Piala Tiger 2005 yang lalu Ketika 55.000 pendukung The Lions mengaum melagukan ole, ole, ole, kami yang berhimpun di tribun timur laut segera menimpalinya dengan lagu yang sama : Impor, impor, impor ! Suporter Singapura di kanan dan kiri kami langsung bungkam.
Nasionalisme kami lagi benar-benar mendidih. Ketika di tengah kami muncul dua cewek bule yang cantik-cantik, mereka jelas mendukung tim Indonesia, koor impor, impor, impor, membahana lagi. Kedua cewek itu ketika tahu jadi sasaran tembak, dituding sebagai suporter impor bagi tim Indonesia, langsung tersenyum kecut. Mereka lari ke tribun yang lebih atas untuk menyelamatkan diri dari “amukan” nasionalisme kami.
Bek tim Singapura Daniel Bennet adalah kelahiran Inggris. Penyerang Agu Casmir dan Itimi Dickson, keduanya berkulit hitam, kelahiran Nigeria. Mereka dinaturalisasi sebagai warga Singapura. Mereka merupakan sosok pemain The Lions yang menjadi sasaran ejekan suporter Indonesia.
Tepat sasarankah ejekan suporter Indonesia tadi ? Di era globalisasi dewasa ini, masih relevankah nasionalisme ? Indonesianis Benedict Anderson pernah menulis betapa arus perpindahan antarbangsa makin menghebat dewasa ini. Ia gambarkan, imperialisme meruyak dari Eropa menyerbu India, Afrika, Asia Tenggara, Oseania dan Karibia. Suku Jawa menyerbu Amerika Latin, Afrika Selatan dan Oseania. Orang Irlandia ke Australia. Jepang ke Brasil. Filipina ke Spanyol. Dan seterusnya.
Kini gereja-gereja ada di Korea, Cina dan Jepang. Bangunan mesjid marak di Manchester Inggris, Marseilles dan Washington DC. Candi Buddha, Hindu atau pun Sikh berdiri di Los Angeles, Toronto, London sampai Dakkar.
Belum lagi gempuran teknologi komunikasi dan informasi yang kini membuat orang mampu menjangkau orang lain di mana pun di dunia. Patrick McGovern dari kelompok penerbit IDG dalam wawancara dengan Newsweek (18/9/1995) bilang bahwa komunitas di masa lalu ditentukan batas-batas geografi. Kini tidak lagi. Contoh : email yang ia terima tiap pagi di New York ada yang dari Beijing, Johannesburg atau Berlin.
“Komunitas saya adalah mereka yang memiliki minat terhadap teknologi informasi. Saya dalam mengambil keputusan berdasarkan tujuan menyejahterakan komunitas saya tersebut, yang tidak terkait struktur politik atau geografi. Dalam konteks ini hadir jenis kepemimpinan politik baru dan nyata melalui komunikasi elektronik. Mereka tidak lain juga gerakan separatis dalam sebuah negara.”
Di Singapura aku mengalami gegar budaya. Kebanggaan nasional Singapura yang populasinya didominasi keturunan etnis Cina, wajahnya diwakili sosok berkulit hitam kelahiran Nigeria. Untuk mendongkrak prestasi tim sepakbola nasional, haramkah bila kita tergiur pula melakukan hal seperti yang dilakukan Singapura ?
Nicholas Negroponte dalam Being Digital (1995) menulis, negara bangsa ibarat kapur barus. Dari bentuk padat yang segera habis menguap menjadi gas. Nasionalisme kemudian hanya ibarat penyakit cacar, yang kini nyaris telah tereradikasi dari muka bumi. Apalagi Albert Einstein pun pernah bilang : nasionalisme adalah penyakit kekanak-kanakan. Nasionalisme adalah penyakit sampar umat manusia !
Aku kini rupanya hidup di jaman yang hebat. Juga membingungkan. Jaman yang juga menakutkan bagi kelangsungan republik yang negara bangsa ini ?
Anda punya pendapat ?
Saya tunggu di : humorliner@yahoo.com.