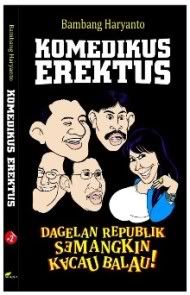Perempuan Sidney Sheldon dan Impian Suporter Sepakbola
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
Kaburnya Empat Biarawati. Spanyol : bumi tempat gairah abadi membuncah dan tak henti-hentinya terjadi pertumpahan darah. Dari aksi balas dendam tiran yang kejam, empat perempuan kabur meninggalkan biara suci, tempat aman mereka berlindung selama ini.
Spain. A land of eternal passion and unceasing bloodshed. From the vengeance of a pitiless tyrant, four women flee the sacred, once-safe walls of the convent.
Empat biarawati itu adalah Graciela, Lucia, Megan dan Teresa. Yang digambarkan memiliki gairah seks membara adalah Lucia. Ia bersembunyi dan masuk biara setelah kabur dari Sisilia, Italia. Ia melarikan diri setelah terlibat dalam aksi pembunuhan yang eksotis dan bergairah, guna membalas dendam atas kematian ayahnya.
Megan adalah anak industrialis kertas Amerika Serikat. Pesawat keluarganya hilang di Spanyol saat ia masih balita. Hanya dia yang selamat. Setelah kabur dari biara yang diobrak-abrik tentara Spanyol, ia terlibat asmara dengan Juan Miro, pentolan pemberontak Basque yang diuber-uber tentara Spanyol.
Kisah indah dan menegangkan dalam novel The Sands of Time (1988) itu seolah mengawang kembali di benak saya, ketika membaca berita di Yahoo News (31/1/2007) bahwa pengarangnya, Sidney Sheldon, telah meninggal dunia.
“Sidney Sheldon yang telah memenangkan penghargaan untuk tiga kariernya, di teater Broadway, film dan televisi, dan pada usia 50 tahun berpindah karier sebagai penulis novel laris tentang perjuangan perempuan yang mampu meraih kejayaan di tengah dunia pria yang kejam, telah meninggal dunia. Ia mencapai usia 89 tahun.”
Karya-karya novelnya menurut Wikipedia antara lain : The Naked Face (1970), The Other Side of Midnight (1973), A Stranger in the Mirror (1976), Bloodline (1977), Rage of Angels (1980), Master of the Game (1982), If Tomorrow Comes (1985), Windmills of the Gods (1987), The Sands of Time (1988), Memories of Midnight (1990), The Doomsday Conspiracy (1991), The Stars Shine Down (1992), Nothing Lasts Forever (1994), Morning, Noon and Night (1995), The Best Laid Plans (1997), Tell Me Your Dreams (1998), The Sky is Falling (2001), Are You Afraid of the Dark? (2004) dan The Other Side Of Me (2005). Sebagian besar sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
Bergantungan Di Tebing. Novel-novel Sheldon digandrungi kaum perempuan. Menanggapi hal ini ia berkomentar, “saya suka menulis kisah tentang perempuan yang berbakat dan cakap, tetapi yang terutama bahwa mereka mempertahankan feminitasnya. Perempuan memiliki kekuatan dahsyat, yaitu feminitasnya, sebab kaum pria tidak memilikinya.”
Sidney Sheldon yang lahir 11 Februari 1917 terkenal piawai mengemas alur ceritanya. Meramunya antara ketegangan tinggi dan sensualitas. “Saya mencoba menulis buku di mana pembaca tidak dapat berhenti untuk merampungkannya,” katanya di tahun 1982. “Saya mencoba mengonstruksi cerita sehingga ketika pembaca sampai di akhir bab, mereka tergerak untuk membaca bab berikutnya. Ini merupakan teknik seri televisi kuno Sabtu malam : meninggalkan sang tokoh bergantungan di bibir tebing pada akhir bab cerita.”
Sheldon membanggakan dirinya terkait otensitas karya-karyanya. Pada tahun 1987 ia berujar : “Kalau saya ingin menulis sesuatu tempat, saya harus mengunjunginya. Apabila saya ingin menulis makanan di Indonesia, saya harus menyantap makanan itu di restoran Indonesia pula. Saya tidak berpikir untuk membohongi pembaca.”
Untuk novelnya Windmills of the Gods, yang menceritakan seluk-beluk CIA, ia melakukan wawncara dengan mantan bos CIA, Richard Helms. Juga melakukan perjalanan ke Argentina dan Rumania, menginap seminggu di Junction City, Kan., di mana tokoh perempuan novelnya itu tinggal.
Pacuan Banteng Gila. Saya bukan penggemar Sidney Sheldon. Saya belum pernah membaca buku-bukunya. Di perpustakaan umum Wonogiri, terdapat setengah lusin novelnya. Satu-satunya novel karya kreator dan sekaligus produser film seri I Dream of Jeannie (1965-1970, di Indonesia ada plagiatnya, “Jinny oh Jinny), saya baca dari cerita bersambung di Harian Kompas. Yaitu The Sands of Time (1988), yang diterjemahkan sebagai Butir-Butir Waktu. Jalinan cerita dalam novel ini ternyata ikut mampu mengantar diri saya memenangkan salah satu penghargaan di tahun 2002.
Salah satu bagian dari Butir-Butir Waktu yang paling saya ingat adalah adegan festival San Fermin di Pamplona, bagian daerah Navarre di Spanyol Utara. Festival seru tersebut yang diselenggarakan setiap bulan Juli diisi dengan aktivitas melepaskan banteng-banteng berlarian ke jalanan kota.

Menabuh Drum Impian. Di tengah syuting pembuatan film dokudrama The Power of Dreams Documentary, saya menabuh drum di tengah suasana menjelang pertandingan sepakbola di Stadion Manahan, Solo, 2002.
Dalam esai berjudul “The Power Of Dreams : Revolusi Mengubah Budaya Suporter Sepakbola Yang Destruktif Menjadi Penghibur Kolosal Yang Atraktif,” untuk mengikuti The Power of Dreams Contest 2002 yang diadakan pabrikan mobil Honda di Indonesia, PT Honda Prospect Motor, telah saya tuliskan impian saya :
“Dengan mengambil tamsil pagelaran adu banteng di Spanyol, banteng dan matador adalah ibarat dua kubu tim sepakbola yang bertanding. Para pemain sepakbola merupakan aktor utama. Sementara penonton tetaplah berstatus sebagai penonton. Mereka bukanlah pemain.
Tetapi di Spanyol juga dikenal atraksi massal, tidak kalah sensasional, yang melibatkan banteng dan massa. Uniknya disini, massa tidak hanya berstatus sebagai penonton, melainkan juga sebagai pemain.
Novelis Sidney Sheldon dalam novel indah dan menegangkan, The Sands of Time, secara memikat menggambarkan operasi pembebasan pentolan gerilyawan separatis Basque dari penjara Spanyol dengan latar belakang adegan pacuan massa dengan banteng “gila” ini. Pembaca disodori panorama eksotis berbau darah, kematian dan juga ruap gairah hidup, saat gemuruh massa dibalut rasa gembira bercampur ngeri, ramai-ramai berlarian di gang-gang sempit kota Pamplona sambil merecoki, menggoda, sekaligus menghindari amukan banteng ganas yang siap menginjak atau menyeruduknya secara buas.
Teater adu banteng di Pamplona ini rasanya klop sebagai presentasi roh teater sepakbola kontemporer, utamanya tren yang menggelombang dan sedang mencari bentuknya yang terbaik di Tanah Air dewasa ini. Penonton, juga suporter, yang dulu hanya duduk manis di bangku-bangku stadion, kini bangkit sebagai aktor yang ikut bermain.
Pada pelbagai kota sepakbola di Tanah Air seperti kota Solo, Jakarta, Malang, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Sleman, Tangerang, Gresik dan Medan, kini mewabah tren suporter sepakbola membentuk organisasi untuk tampil sebagai sosok entertainer, penghibur, dalam konser sepakbola. Secara atraktif kerumunan massa itu kompak meneriakkan yel-yel, melakukan koor, juga menampilkan koreografi yang gigantik.
Akibatnya perbedaan status sebagai entertainer, antara pemain sepakbola dan suporter, kini tak lagi kontras. Keduanya berbaur, saling berdialog, guna “membakar” atmosfir pertandingan sepakbola sehingga menjadi tontonan yang benar-benar menggairahkan. Atensi publik yang semula menjadi privilege pemain, kini sebagiannya terenggut oleh aksi suporter yang melakukan konser di pinggir lapangan secara signifikan !
Paradigma baru ini membuka harapan baru, sebagai salah satu antidote, penangkal, bagi rentannya sepakbola dengan aksi-aksi rusuh suporter. Peningkatan status suporter dari sekadar properti menjadi aktor harus disadari merupakan outlet, penyaluran, yang sehat dan rasional guna mensubstitusi fokus perhatian suporter yang mudah meledak terpicu oleh perolehan skor akhir, atau status kalah-menang dari tim yang didukungnya. Pemikiran ini bukankah sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh gerakan Olimpiade, bahwa partisipasi itu lebih penting dibandingkan dengan kemenangan ?
Para suporter dalam status sebagai entertainer pada langkah berikutnya didorong agar bertanggung jawab secara profesional terhadap kualitas konsernya. Sedang kalah atau menang, itu urusan profesional tim kesebelasan bersangkutan. Dalam konteks ini kelompok suporter harus terus memacu kreativitas, hingga suguhan konsernya menghibur, tak kalah sensasional dari pertandingan sepakbolanya. Mereka juga harus terampil menjual diri sehingga mampu merenggut atensi dan liputan media !”
Impian Belum Berakhir. Di Jakarta, tanggal 6-8 April 2002, di hadapan dewan juri yang terdiri Arswendo Atmowiloto, Mien Uno, Riri Riza, Susi Susanti, Kusnadi Budiman dan Satoshi Okamoto, saya mempresentasikan impian besar saya sebagai suporter sepakbola Indonesia.
Adalah suatu kehormatan besar, sebagai pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli (2000) dan tercatat di Museum Rekor Indonesia (“semoga foto saya masih terpajang di museum tersebut di Srondol, Semarang”), saya bisa meresapi makna kekuatan impian yang dikukuhi oleh Soichiro Honda, pendiri kerajaan otomotif Honda. Saya memenangkan kontes tersebut. Profil diri saya sebagai suporter sepakbola kemudian ditayangkan di TransTV, 29 Juli 2002.
Di Wonogiri sekarang ini, hiruk pikuk dunia suporter sepakbola sudah saya tinggalkan. Tetapi saya masih memikirkannya, mengaduk-aduk gagasan, dan menuliskannya. Sejak tahun 2003 saya mengelola blog Suporter Indonesia, sebagai kontributor untuk majalah sepakbola Freekick (Jakarta), menulis untuk tabloid Liga Indonesia, dan bulan lalu (5/1/2007) sempat menjadi nara sumber via telepon untuk perbincangan seputar suporter sepakbola di Radio Utan Kayu (Jakarta).
Dalam perbincangan radio tersebut saya mengatakan bahwa kelompok suporter sepakbola Indonesia masih memiliki cakrawala yang sempit. Mereka terlalu fanatik untuk membela daerahnya, tetapi tidak melihat kanvas besar dunia sepakbola Indonesia yang terus terpuruk prestasinya di tataran regional, apalagi di tingkat dunia.
Impian saya untuk mengubah paradigma suporter sepakbola yang antara lain embrio gagasannya dipantik oleh sebagian isi novelnya Sidney Sheldon, masih dibutuhkan lagi ribuan sampai jutaan butir-butir waktu untuk realisasinya.
Wonogiri, 4-5 Februari 2007
si
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
Kaburnya Empat Biarawati. Spanyol : bumi tempat gairah abadi membuncah dan tak henti-hentinya terjadi pertumpahan darah. Dari aksi balas dendam tiran yang kejam, empat perempuan kabur meninggalkan biara suci, tempat aman mereka berlindung selama ini.
Spain. A land of eternal passion and unceasing bloodshed. From the vengeance of a pitiless tyrant, four women flee the sacred, once-safe walls of the convent.
Empat biarawati itu adalah Graciela, Lucia, Megan dan Teresa. Yang digambarkan memiliki gairah seks membara adalah Lucia. Ia bersembunyi dan masuk biara setelah kabur dari Sisilia, Italia. Ia melarikan diri setelah terlibat dalam aksi pembunuhan yang eksotis dan bergairah, guna membalas dendam atas kematian ayahnya.
Megan adalah anak industrialis kertas Amerika Serikat. Pesawat keluarganya hilang di Spanyol saat ia masih balita. Hanya dia yang selamat. Setelah kabur dari biara yang diobrak-abrik tentara Spanyol, ia terlibat asmara dengan Juan Miro, pentolan pemberontak Basque yang diuber-uber tentara Spanyol.
Kisah indah dan menegangkan dalam novel The Sands of Time (1988) itu seolah mengawang kembali di benak saya, ketika membaca berita di Yahoo News (31/1/2007) bahwa pengarangnya, Sidney Sheldon, telah meninggal dunia.
“Sidney Sheldon yang telah memenangkan penghargaan untuk tiga kariernya, di teater Broadway, film dan televisi, dan pada usia 50 tahun berpindah karier sebagai penulis novel laris tentang perjuangan perempuan yang mampu meraih kejayaan di tengah dunia pria yang kejam, telah meninggal dunia. Ia mencapai usia 89 tahun.”
Karya-karya novelnya menurut Wikipedia antara lain : The Naked Face (1970), The Other Side of Midnight (1973), A Stranger in the Mirror (1976), Bloodline (1977), Rage of Angels (1980), Master of the Game (1982), If Tomorrow Comes (1985), Windmills of the Gods (1987), The Sands of Time (1988), Memories of Midnight (1990), The Doomsday Conspiracy (1991), The Stars Shine Down (1992), Nothing Lasts Forever (1994), Morning, Noon and Night (1995), The Best Laid Plans (1997), Tell Me Your Dreams (1998), The Sky is Falling (2001), Are You Afraid of the Dark? (2004) dan The Other Side Of Me (2005). Sebagian besar sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
Bergantungan Di Tebing. Novel-novel Sheldon digandrungi kaum perempuan. Menanggapi hal ini ia berkomentar, “saya suka menulis kisah tentang perempuan yang berbakat dan cakap, tetapi yang terutama bahwa mereka mempertahankan feminitasnya. Perempuan memiliki kekuatan dahsyat, yaitu feminitasnya, sebab kaum pria tidak memilikinya.”
Sidney Sheldon yang lahir 11 Februari 1917 terkenal piawai mengemas alur ceritanya. Meramunya antara ketegangan tinggi dan sensualitas. “Saya mencoba menulis buku di mana pembaca tidak dapat berhenti untuk merampungkannya,” katanya di tahun 1982. “Saya mencoba mengonstruksi cerita sehingga ketika pembaca sampai di akhir bab, mereka tergerak untuk membaca bab berikutnya. Ini merupakan teknik seri televisi kuno Sabtu malam : meninggalkan sang tokoh bergantungan di bibir tebing pada akhir bab cerita.”
Sheldon membanggakan dirinya terkait otensitas karya-karyanya. Pada tahun 1987 ia berujar : “Kalau saya ingin menulis sesuatu tempat, saya harus mengunjunginya. Apabila saya ingin menulis makanan di Indonesia, saya harus menyantap makanan itu di restoran Indonesia pula. Saya tidak berpikir untuk membohongi pembaca.”
Untuk novelnya Windmills of the Gods, yang menceritakan seluk-beluk CIA, ia melakukan wawncara dengan mantan bos CIA, Richard Helms. Juga melakukan perjalanan ke Argentina dan Rumania, menginap seminggu di Junction City, Kan., di mana tokoh perempuan novelnya itu tinggal.
Pacuan Banteng Gila. Saya bukan penggemar Sidney Sheldon. Saya belum pernah membaca buku-bukunya. Di perpustakaan umum Wonogiri, terdapat setengah lusin novelnya. Satu-satunya novel karya kreator dan sekaligus produser film seri I Dream of Jeannie (1965-1970, di Indonesia ada plagiatnya, “Jinny oh Jinny), saya baca dari cerita bersambung di Harian Kompas. Yaitu The Sands of Time (1988), yang diterjemahkan sebagai Butir-Butir Waktu. Jalinan cerita dalam novel ini ternyata ikut mampu mengantar diri saya memenangkan salah satu penghargaan di tahun 2002.
Salah satu bagian dari Butir-Butir Waktu yang paling saya ingat adalah adegan festival San Fermin di Pamplona, bagian daerah Navarre di Spanyol Utara. Festival seru tersebut yang diselenggarakan setiap bulan Juli diisi dengan aktivitas melepaskan banteng-banteng berlarian ke jalanan kota.

Menabuh Drum Impian. Di tengah syuting pembuatan film dokudrama The Power of Dreams Documentary, saya menabuh drum di tengah suasana menjelang pertandingan sepakbola di Stadion Manahan, Solo, 2002.
Dalam esai berjudul “The Power Of Dreams : Revolusi Mengubah Budaya Suporter Sepakbola Yang Destruktif Menjadi Penghibur Kolosal Yang Atraktif,” untuk mengikuti The Power of Dreams Contest 2002 yang diadakan pabrikan mobil Honda di Indonesia, PT Honda Prospect Motor, telah saya tuliskan impian saya :
“Dengan mengambil tamsil pagelaran adu banteng di Spanyol, banteng dan matador adalah ibarat dua kubu tim sepakbola yang bertanding. Para pemain sepakbola merupakan aktor utama. Sementara penonton tetaplah berstatus sebagai penonton. Mereka bukanlah pemain.
Tetapi di Spanyol juga dikenal atraksi massal, tidak kalah sensasional, yang melibatkan banteng dan massa. Uniknya disini, massa tidak hanya berstatus sebagai penonton, melainkan juga sebagai pemain.
Novelis Sidney Sheldon dalam novel indah dan menegangkan, The Sands of Time, secara memikat menggambarkan operasi pembebasan pentolan gerilyawan separatis Basque dari penjara Spanyol dengan latar belakang adegan pacuan massa dengan banteng “gila” ini. Pembaca disodori panorama eksotis berbau darah, kematian dan juga ruap gairah hidup, saat gemuruh massa dibalut rasa gembira bercampur ngeri, ramai-ramai berlarian di gang-gang sempit kota Pamplona sambil merecoki, menggoda, sekaligus menghindari amukan banteng ganas yang siap menginjak atau menyeruduknya secara buas.
Teater adu banteng di Pamplona ini rasanya klop sebagai presentasi roh teater sepakbola kontemporer, utamanya tren yang menggelombang dan sedang mencari bentuknya yang terbaik di Tanah Air dewasa ini. Penonton, juga suporter, yang dulu hanya duduk manis di bangku-bangku stadion, kini bangkit sebagai aktor yang ikut bermain.
Pada pelbagai kota sepakbola di Tanah Air seperti kota Solo, Jakarta, Malang, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Sleman, Tangerang, Gresik dan Medan, kini mewabah tren suporter sepakbola membentuk organisasi untuk tampil sebagai sosok entertainer, penghibur, dalam konser sepakbola. Secara atraktif kerumunan massa itu kompak meneriakkan yel-yel, melakukan koor, juga menampilkan koreografi yang gigantik.
Akibatnya perbedaan status sebagai entertainer, antara pemain sepakbola dan suporter, kini tak lagi kontras. Keduanya berbaur, saling berdialog, guna “membakar” atmosfir pertandingan sepakbola sehingga menjadi tontonan yang benar-benar menggairahkan. Atensi publik yang semula menjadi privilege pemain, kini sebagiannya terenggut oleh aksi suporter yang melakukan konser di pinggir lapangan secara signifikan !
Paradigma baru ini membuka harapan baru, sebagai salah satu antidote, penangkal, bagi rentannya sepakbola dengan aksi-aksi rusuh suporter. Peningkatan status suporter dari sekadar properti menjadi aktor harus disadari merupakan outlet, penyaluran, yang sehat dan rasional guna mensubstitusi fokus perhatian suporter yang mudah meledak terpicu oleh perolehan skor akhir, atau status kalah-menang dari tim yang didukungnya. Pemikiran ini bukankah sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh gerakan Olimpiade, bahwa partisipasi itu lebih penting dibandingkan dengan kemenangan ?
Para suporter dalam status sebagai entertainer pada langkah berikutnya didorong agar bertanggung jawab secara profesional terhadap kualitas konsernya. Sedang kalah atau menang, itu urusan profesional tim kesebelasan bersangkutan. Dalam konteks ini kelompok suporter harus terus memacu kreativitas, hingga suguhan konsernya menghibur, tak kalah sensasional dari pertandingan sepakbolanya. Mereka juga harus terampil menjual diri sehingga mampu merenggut atensi dan liputan media !”
Impian Belum Berakhir. Di Jakarta, tanggal 6-8 April 2002, di hadapan dewan juri yang terdiri Arswendo Atmowiloto, Mien Uno, Riri Riza, Susi Susanti, Kusnadi Budiman dan Satoshi Okamoto, saya mempresentasikan impian besar saya sebagai suporter sepakbola Indonesia.
Adalah suatu kehormatan besar, sebagai pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli (2000) dan tercatat di Museum Rekor Indonesia (“semoga foto saya masih terpajang di museum tersebut di Srondol, Semarang”), saya bisa meresapi makna kekuatan impian yang dikukuhi oleh Soichiro Honda, pendiri kerajaan otomotif Honda. Saya memenangkan kontes tersebut. Profil diri saya sebagai suporter sepakbola kemudian ditayangkan di TransTV, 29 Juli 2002.
Di Wonogiri sekarang ini, hiruk pikuk dunia suporter sepakbola sudah saya tinggalkan. Tetapi saya masih memikirkannya, mengaduk-aduk gagasan, dan menuliskannya. Sejak tahun 2003 saya mengelola blog Suporter Indonesia, sebagai kontributor untuk majalah sepakbola Freekick (Jakarta), menulis untuk tabloid Liga Indonesia, dan bulan lalu (5/1/2007) sempat menjadi nara sumber via telepon untuk perbincangan seputar suporter sepakbola di Radio Utan Kayu (Jakarta).
Dalam perbincangan radio tersebut saya mengatakan bahwa kelompok suporter sepakbola Indonesia masih memiliki cakrawala yang sempit. Mereka terlalu fanatik untuk membela daerahnya, tetapi tidak melihat kanvas besar dunia sepakbola Indonesia yang terus terpuruk prestasinya di tataran regional, apalagi di tingkat dunia.
Impian saya untuk mengubah paradigma suporter sepakbola yang antara lain embrio gagasannya dipantik oleh sebagian isi novelnya Sidney Sheldon, masih dibutuhkan lagi ribuan sampai jutaan butir-butir waktu untuk realisasinya.
Wonogiri, 4-5 Februari 2007
si